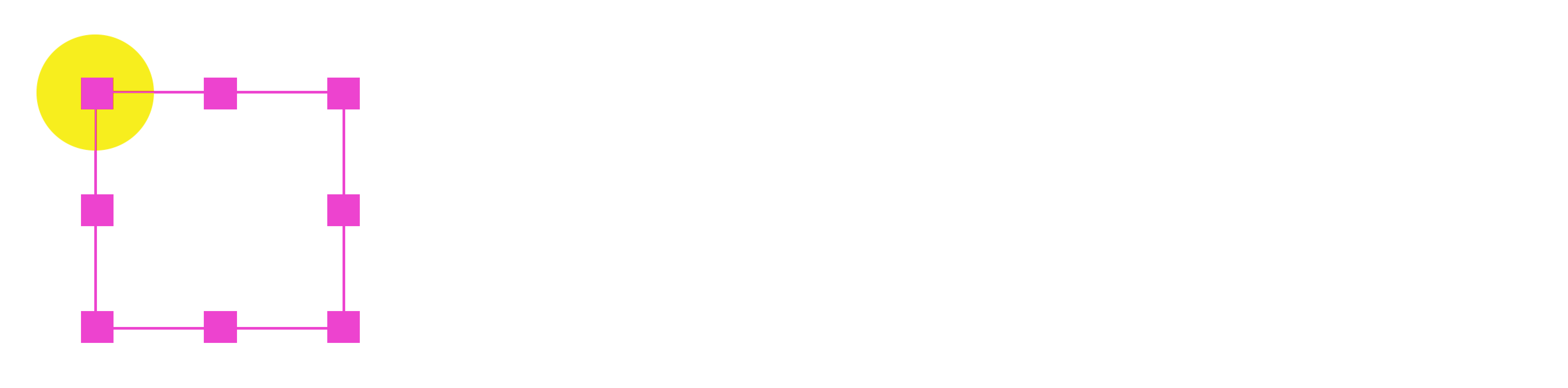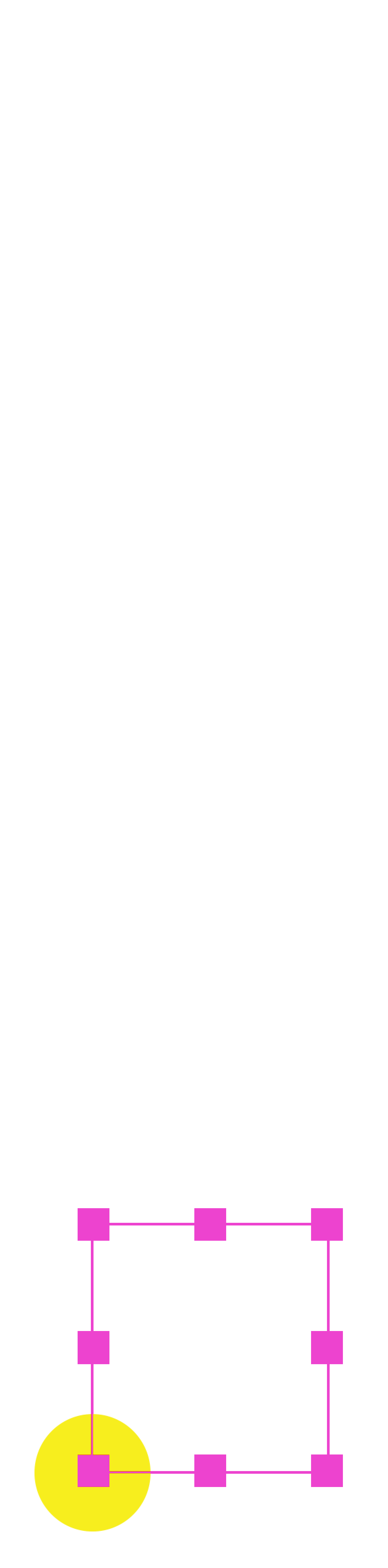All poems are in Indonesian. Click to read summary in English. Keempat puisi ini adalah…
Nonton dan Ngopi: Ngasak Cerita dari Ladang Kebudayaan
Seniman Coffee Resident: Hardiwan Prayoga – Minikino

Pernahkah kita mendengar ucapan Insya Allah, Astaghfirullah, atau Bismillahirrahmanirrahim keluar dari mulut seorang non-muslim? Kalau iya, kesan dan perasaan apa yang seketika muncul dalam benakmu?
Film Berdoa, Mulai karya Tanzilal Azizie, bercerita tentang isu agama pada remaja pelajar di kelas menengah perkotaan. Film ini menggambarkan bagaimana menjadi minoritas di tengah berbagai narasi dan aktivitas agama mayoritas yang merasuk pada ruang kelas/publik hingga ruang privat. Kenyataan yg tidak bisa ditolak oleh Ruth, si protagonis utama, sampai akhirnya secara tidak sadar menjalankan laku ala agama mayoritas meski hanya secara fisik, entah secara filosofis. Kenapa Berdoa, Mulai? Film ini sangat pas untuk jadi film pendek. Fokus dan cukup elaboratif dalam menyampaikan konflik. Seluruhnya disampaikan dalam bahasa sinematik rapi dan storytelling yang efektif.

Still foto film ‘berdoa mulai’
Selain itu, banyak film dalam Indonesia Raja 2023 yang ada dalam posisi tanggung., antara terlalu panjang atau terlalu pendek. Terlalu panjang sehingga bertele-tele dan kehilangan fokus karena tumpukan layer konflik yang gagal disusun dengan baik. Ada juga beberapa film yang terlalu pendek, sehingga konten cerita tidak terelaborasi lebih dalam, sehingga hanya terlihat problem pada layer pertama. Singkatnya gagal menangkap masalah sosial sebagai problem struktural. Akibatnya penonton beranggapan bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam tatanan masyarakat disebabkan semata oleh kecacatan moral warga saja, padahal tentu tidak sesederhana itu.
Sepertinya para pembuat film kerap melewatkan perhatiannya pada film sebagai karya seni durational. Sehingga efektivitas bercerita dan ketelitian untuk fokus pada konflik dengan tetap elaboratif tanpa terjebak dalam tumpukan layer problem yang membingungkan dirinya sendiri adalah perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam proses produksi film selain imajinasi dan keberanian untuk berpihak.
Selain problem durational, ada juga beberapa film yang berhenti ketika menemukan cerita/ subjek yang unik. Merasa cukup dengan keunikan tersebut, film-film semacam ini berujung dengan gagal menggali konteks dan berakhir begitu saja tanpa diberi olahan sinematik yang seharusnya ada lah dikit-dikit sentuhan craftmanship-nya, gitu lho. Ada juga yang terlalu sibuk bereksperimen pada aspek sinematik sampai lupa pada persoalan etika representasi, terutama pada film-film dengan isu kekerasan seksual.
Baca juga: Kehidupan bertetangga dan kopi.
Berdoa, Mulai membicarakan tentang agama, sebagai persoalan yang hari ini semakin sering dibicarakan di ruang publik. Biasanya film dengan tema ini akan terjebak dalam formulasi yang penuh dengan stigma, stereotip dan cenderung klise, apalagi kalau diakhiri dengan ceramah moral soal toleransi…. Huekkk malesss. Dibalik itu semua, Berdoa, Mulai berhasil untuk setidaknya lepas dari terjebak dalam masalah klasik tersebut. Mulai dari kehadiran Ruth sebagai, kalau kata Sting “Englishman in New York” di sekolah yg penuh dengan narasi-narasi islami dari berdoa hingga pelajaran di kelas, hingga suara sholawat yang kehilangan kemerduannya akibat berebut microphone. Adegan berebut microphone membawaku pada konteks soal bagaimana Islam selalu melibatkan kontestasi kuasa soal siapa yang paling memiliki akses pada media yang mampu menyiarkan ‘kebenaran’-nya. Sebuah obsesi pada kekuasaan yang sangat tidak perlu dan justru membuat Islam kehilangan nilai rahmatan lil alamin sebagaimana yang disampaikan ibu guru di kelas.
Bagian paling ‘kurang ajar’ menurutku adalah adegan ketika ibu guru bicara tentang bagaimana umat Islam kerap dicitrakan sebagai pemarah, intoleran dan teroris. Kemudian dilanjutkan dengan shot yang memperlihatkan poster stop merokok karena rokok bagaikan bom waktu yang akan membunuhmu. Menyandingkan keduanya memberikan interpretasi, apakah rokok dan Islam sama-sama berbahaya karena bisa saja keduanya menjadi bom waktu dan meledak kala tiba masanya? Eh bahaya ga sih nulis gini… hehehe…

Still foto film ‘berdoa mulai’
Pada hari pertama kedatanganku di MASH Denpasar, Edo Wulia bercerita soal bagaimana film pendek sejatinya pondasi penting dari keberlangsungan industri film. Singkatnya, jika ruang apresiasi bagi film pendek tidak tergarap dengan serius, industri film sebenarnya berdiri di atas bangunan yang mudah runtuh. Entah karena dihantam pandemi, gempuran film impor, atau pergeseran media menonton. Dari cara Edo bercerita, aku justru menangkap kesan bahwa Minikino memaknai film pendek lebih dari itu. Jika melihat reputasi dan konsistensi Minikino, film pendek bagi mereka adalah sebuah ideologi, sebuah gerakan.
Ada jenis-jenis perasaan, pengalaman, dan keberpihakan yang memang paling tepat jika diwujudkan dan disampaikan lewat format film pendek. Berdoa, Mulai bagiku adalah contoh terbaik untuk menggambarkan penyataan yang kumaksud barusan. Berdoa, Mulai adalah film pendek yang pas, tidak tanggung, menunjukkan keberpihakan yang jelas, dan berdiri di atas jalinan lapisan konflik yang tidak menyakiti pikiran. Dengan kata lain, berbagai aspek formal film pendek khususnya pada durasi, menunjukkan nilai esensialnya yang khas. Nilai yang tidak bisa digantikan oleh format film-film lainnya. Apalagi film yang harus bernegosiasi dengan berbagai hal di luar urusan film itu sendiri.
Serupa tapi tak sama, kopi juga bagiku memiliki nilai esensial yang tidak bisa digantikan oleh jenis minuman lainnya. Kopi juga sebagaimana film, dua entitas yang sama-sama dipengaruhi dengan sangat besar oleh intervensi manusia. Sudah disampaikan di atas bagaimana film kadang berhenti pada penemuan cerita/subjek unik. Kopi juga tidak dapat dihidangkan sebagai minuman dengan rasa khas tanpa kemampuan manusia menyampaikan rasa yang ingin dibagi pada penikmatnya. Akhirnya kopi tidak hanya memiliki unsur biologis, tetapi juga kultural dan ekonomi-politik. Dari sini satu hal yang perlu dicatat, kekhasan dari sebuah kopi bukan dalam rangka menyeragamkan rasa dan cara menikmatinya. Sebagaimana film yang juga memiliki ranah dan ruangnya masing-masing, begitu pula kopi.
Jika Berdoa, Mulai berkisah tentang keberagaman yang merasuk dalam bawah sadar justru membuat kita luwes membolak-balikkan dan melintasi batas-batasnya, kopi juga memiliki ratusan ragam, ratusan peracik kopi, dan juga barangkali ratusan cara menikmatinya. Lantas apa yang terpenting antara keduanya? Kalau menurutku yang terpenting adalah kejujuran untuk menyampaikan rasa pada orang lain, sekaligus keterbukaan pada penerimaan dan ragam apresiasinya.

Sesi cupping kopi
Sejujurnya sulit bagiku mencari kopi dengan rasa yang selaras dengan pengalaman menonton Berdoa, Mulai. Ternyata setelah coba kurenungkan lebih dalam, pengalaman paling berkesan selama 5 hari residensi di Toko Seniman adalah pengalaman cupping 5 jenis kopi pada Jumat 23 Juni. Bukan pada rasa yang sejujurnya sulit aku identifikasi perbedaan satu sama lainnya, melainkan pada cupping menuntut kita melakukan berbagai laku-laku gestural yang khas. Ingatan ini terpanggil kembali kurang lebih 13 jam setelah cupping, tepatnya pada jumat jam 23.00, ketika kau ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat itu, ternyata kencingku masih berbau kopi! Aroma yang begitu persis dengan kopi-kopi yang kucoba bersama Insan siang harinya. Ketika isi kepalaku sudah memikirkan hal lain, ternyata tubuhku masih mengingat dengan cukup tajam pengalaman dan perasaan yang terekam ketika cupping.
Nah, pada titik inilah aku menyadari dimensi lain soal bagaimana film bekerja pada pikiran manusia. Sebagaimana pengalaman cupping yang ternyata memorable, menonton Berdoa, Mulai juga memanggil kembali berbagai ingatan dan segudang pertanyaanku tentang spiritualitas dan keyakinan. Pada akhirnya aku menawarkan varian kopi cold brew milky way untuk menemani kawan-kawan menonton dan berbincang soal agama dan keyakinan yang direfleksikan dengan riang gembira. Ada kalanya diskusi perkara ini begitu tegang dan intens. Namun lewat Berdoa, Mulai kita memanggil kembali kehangatan, keramahan, dan penerimaan pada berbagai perbedaan.

Milky way cold brew kopi susu
Penutup
Selama ini kita kerap membicarakan kopi pada soal rasa. Pun tidak jarang membicarakan film dari kesan-kesan yang muncul seketika. Dari residensi ini aku belajar hal baru, bahwa rasa tidak pernah hadir dari ruang hampa. Barangkali indrawi kita bisa dikelabui oleh berbagai sugesti soal rasa, tetapi tubuh dan ingatanmu akan merekam hal-hal yang kerap luput dari perhatian. Yaitu bagaimana segala penilaian kita atas rasa bekerja dalam struktur dan konstruksi sosial.
Nonton dan ngopi, dua aktivitas ini bisa membawa kita pada dimensi pengalaman yang lebih dalam. Memeriksa dan memungut kepingan memori yang tercecer, berserak dan diabaikan. Laku ini yang aku ibaratkan sebagai ngasak. Ngasak adalah bahasa jawa yang berarti mencari sisa padi hasil panen. Nonton dan ngopi adalah sebuah kerja ngasak berbagai hal yang sering luput dari pembicaraan tentang kebudayaan dan identitas yang selama ini melulu ditafsirkan oleh kepentingan pasar
Baca juga: No word for aftertaste
Penulis merupakan salah satu dari empat peserta program Artist Residency kerja sama antara Seniman Residency dengan Minikino dan Mash Denpasar yang dilaksanakan di Denpasar pada 6 Juni sampai 2 Juli. Selangkapnya tentang program ini, kunjungi: https://minikino.org/xtokoseniman/
Apa itu Seniman Coffee Residensi? Program ini mengajak para pegiat kopi, artis, designer, penulis, dll untuk melakukan eksplorasi tentang kopi. Peserta boleh memiliki background kopi maupun tidak. Cari tahu lebih lanjut di: Seniman Residency
.
NOTES
“Emotions neither belong to, or are manufactured by, discrete individuals. Rather, emotions are formed through social exchange.” (Ahmed, Sara. “Affective Economies.” Social Text 79 22.2 (2004): 117-139)
The imperial archive can be described as an archive of unhappiness. Colonial knowledges constitute the other as not only an object of knowledge, a truth to be discovered, but as being unhappy, as lacking the qualities or attributes required for a happier state of existence (Ahmed, Sara. Promise 125).
Coffee is a palimpsestic cultural site at which to explore the ways in which the politics of good feeling obscure discomforting and complex questions of power, exploitation, and disadvantage in global economies of coffee production and consumption.
Long term relationships, imagined as virtuous despite the opacity of the negotiation procedure in most cases, narrates the conviction that relationship in and of itself is a good in what might be called the colonial redramatisation staked by an affective coffee economy.
Sara Ahmed’s words; so you make the trip to origin, and you know “just” what to pay for this bean and that. Failure to know this “just” is often felt as a failure of care. But, for whom? (Sunderland, S. (2012). Trading the Happy Object: Coffee, Colonialism, and Friendly Feeling. M/C Journal, 15(2). https://doi.org/10.5204/mcj.473)